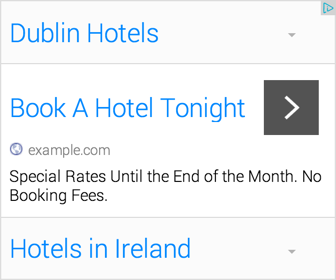
Sejarah Perkembangan Tasawuf
Benih ilmu tasawuf bermula pada masa
khalifah ketiga, yakni ketika terjadi peristiwa
tragis dalam pembunuhan Utsman Ibn Affan ra, hal ini berimplikasi terjadinya kekacauan dan kerusakan
terhadap sebagian kaum muslimin. Oleh sebab itu para sahabat dan pemuka Islam
berfikir untuk membangkitkan kembali ajaran Islam dengan berikhtiar kembali ke
masjid (I’tikaf) dan mendengarkan kisah mengenai targhib dan tarhib
tentang keindahan hidup zuhud.[1] Dalam
sejarah perkembangannya, terdapat masa atau tahapan yang terjadi terhadap ilmu
Tasawuf, beberapa masa tersebut adalah masa pembentukan, pengembangan,
konsolidasi, falsafi, dan masa pemurnian.[2] Berikut adalah penjelasan tiap-tiap perkembangan ilmu Tasawuf:
a. Masa
Pembentukan
Masa ini terjadi dalam abad I dan
abad II hijriah, Hasan Basri dan Rabiah Adawiyah muncul dengan ajaran khauf dan
cinta, yakni mempertebal takut atau taqwa kepada Tuhan, penyucian hubungan
manusia dengan Tuhan, selain itu muncul gerakan pembaharuan hidup kerohanian
dikalangan kaum muslimin. Dalam ajaran-ajaran yang dikemukakan, dianjurkan
mengurangi makan (Ju’), menjauh dari
keramaian duniawi (Zuhud), dan
mencela dunia (Dzammu al dunya).[3]
Selanjutnya pada abad II Hijriah,
Tasawuf tidak banyak berbeda dengan sebelumnya, meskipun penyebabnya berbeda.
Penyebab pada abad ini terjadi karena formalism dalam melakukan syariat agama
(lebih bercorak fiqh) yang menyebabkan sebagian orang tidak puas dengan
kehidupannya. Abu al-Wafa menyimpulkan, bahwa zuhud Islam pada abad I dan II
hijriyah mempunyai karakter sebagai berikut:[4]
a. Menjauhkan diri
dari dunia menuju ke akhirat yang berakar pada nas agama yang dilatarbelakangi
oleh sosiopolitik yang bertujuan meningkatkan moral.
b. Bersifat
praktis, para pendirinya tidak menaruh perhatian untuk menyusun prinsip-prinsip
teoritis atas kezuhudannya itu. Sedangkan sarana praktisnya adalah hidup dalam
ketenangan dan kesederhanaan secara penuh, sedikit makan maupun minum, banyak
beribadah dan mengingat Allah SWT. dan berlebih-lebihan dalam merasa
berdosa, tunduk mutlak kepada kehendak-Nya, dan berserah diri kepada-Nya.
Tasawuf pada masa ini mengarah pada tujuan moral.
c. Motif zuhudnya
ialah rasa takut, yaitu rasa yang muncul dari landasan amal keagamaan secara
sungguh-sungguh. Sementara pada akhir abad II Hijriyah, di tangan Rabi’ah
al-Adawiyah muncul motif rasa cinta, yang bebas dari rasa takut terhadap
adhab-Nya maupun harapan terhadap pahala-Nya. Hal ini dicerminkan lewat
penyucian diri, dan abstraksi dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan.
d.
Menjelang akhir
abad II Hijriyah, sebagian zahid, khususnya di Khurasan, dan Rabi’ah
al-Adawiyah ditandai kedalaman membuat analisa, yang bisa dipandang sebagai
fase pendahuluan tasawuf, atau cikal bakal para pendiri tasawuf falsafi abad
III dan IV Hijriyah.
b. Masa Pengembangan
Pada abad III dan IV,
tasawuf sudah bercorak kefana’an (ekstase) yang menjurus ke persatuan hamba dengan
Khalik. Orang sudah ramai membahas tentang lenyap dalam kecintaan (fana’fi al-Mahbub), bersatu dengan
kecintaan (ittihad bi al-Mahbub), kekal dengan Tuhan (baqa’ bi al-Mahbub), menyaksikan Tuhan (musyahadah), bertemu dengan-Nya (liqa’) dan menjadi satu dengan-Nya (‘ain al- jama’) seperti yang
diungkapkan oleh Abu Yazid al-Bushtham (261 H), seorang sufi dari Persia yang
pertama kali mempergunakan istilah fana’
(lebur atau hancurnya perasaan) sehingga dia dianggap sebagai peletak
batu pertama dalam aliran ini. Sesudah Abu Yazid al-Busthami, lahirlah seorang
sufi kenamaan, yakni al-Hallaj (309 H) yang menampilkan teori al-Hulul
(reinkarnasi Tuhan).
Al-Thusi dalam al-Luma’nya
menyatakan bahwa hulul adalah[5]:
“Allah memilih suatu jisim yang
ditempati ma’na rububiyyah dan leburlah daripadanya ma’na basyariyyah.”
Menurut al-Hallaj, manusia
mempunyai dua sifat, yakni sifat kemanusiaan (nasut) dan sifat ketuhanan (lahut).
Pada akhir abad ke III orang berlomba-lomba menyatakan dan mempertajam
pemikirannya tentang kesatuan penyaksian (Wahdat
al-Syuhud), kesatuan kejadian (wahdat al-Wujud) kesatuan agama-agama (Wahdat
al- Adyan), berhubungan dengan
Tuhan (ittishal), keindahan dan
kesempurnaan Tuhan (Jamal dan Kamal), manusia sempurna (insan kamil), yang
kesemuanya itu tak mungkin dicapai oleh para Sufi kecuali dengan latihan yang
teratur (riyadhah). Kemudian muncul
Junaidi al-Baghdady meletakkan dasar-dasar ajaran tasawuf dan thariqah, cara
mengajar dan belajar ilmu tasawuf, syekh, mursyid,
murid dan murad, sehingga dia mendapat predikat Syekh
al-Thaifah (ketua rombongan suci).
Tasawuf pada masa ini sudah
berkembang menjadi madzhab, bahkan seolah sebuah agama yang berdiri sendiri.
Pada abad ke III dan IV Hijriah terdapat dua aliran Tasawuf, yakni Tasawuf
Sunni yang memagari diri dengan Al-Qur’an dan al-Hadits dengan mengaitkan dan tingkatan
rohani pada keduanya. Serta Tasawuf Semi Falsafi yang lebih cenderung pada
ungkapan ganjil serta bertolak dari keadaan fana’ terhadap pernyataan penyatuan-penyatuan (ittihad atau hulul).
c. Masa Konsolidasi
Pada
abad V Hijriah, diadakan konsolidasi antara kedua aliran pada masa sebelumnya,
hal ini ditandai dengan aanya kompetisi antar keduanya, yang kemudian
dimenangkan tasawuf sunni dan menenggelamkan tasawuf falsafi. Dengan adanya
kompetisi tersebut, pada masa ini tasawuf dinilai mengadakan pembaharuan ,
yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke dalam
landasan al-Qur’an dan al-Hadits. Tokoh-tokoh pada masa ini adalah ialah
al-Qusyairi (376-465 H), Al-Harawi (396 H), dan al-Ghazali (450-505 H).
al-Qusyairi (376-465 H) terkenal sebagai pembela teologi Ahlussunnah wal
Jama’ah, beliau mampu mengompromikan antara syariah dan hakikah
berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadits. Beliau menekankan bahwa kesehatan
batin dengan berpegang teguh pada keduanya lebih penting daripada pakaian
lahiriah.[6]
Al-Harawi
(396 H), sikapnya tegas dan tandas terhadap tasawuf, beliau menganggap orang
yang suka mengeluarkan syathahat , hatinya tidak bisa tenteram atau
dengan kata lain, syathahat itu muncul dari ketidaktenangan. Sebab apabila
ketenangan itu terpaku dalam kalbu mereka, akan membuat seseorang terhindar
dari keganjilan ucapan atau pun segala penyebabnya. Al-Ghazali (450-505 H),
memilih Tasawuf Sunni berdasarkan doktrin Ahlussunnah walJama’ah, corak
tasawufnya bersifat psiko-moral yang mengutamakan pendidikan moral. Beliau
menilai negative terhadap syathahat, karena dua kelemahan yang dimilikinya,
yaitu kurang memperhatikan kepada amal lahiriah serta keganjilan makna yang
tidak dipahami maknanya.
d. Masa Falsafi
Pada abad IV Hijriah, muncullah tasawuf falsafi atau
tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, yang dikompromikan dengan
pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Ibn
Khaldun dalam Muqaddimahnya menyimpulkan, bahwa tasawuf falsafi mempunyai
empat obyek utama, dan menurut Abu al-Wafa bisa dijadikan karakter sufi
falsafi, yaitu :
a.
Latihan
rohaniah dengan rasa, intuisi serta introspeksi yang timbul darinya,
b.
Iluminasi
atau hakikat yang tersingkap dari alam ghaib.
c.
Peristiwa-peristiwa
dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau
keluar biasaan.
d. Penciptaan
ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar (syathahiyat).
Selanjutnya, pada abad VI dan VII hijriah, muncul cikal bakal orde (tarekat)
sufi kenamaan, seperti tarekat Qadariyah, Suhrawardiyah, Rifa‟iyah,
Syadziliyah, Badawiyah dan tarekat Naqsyabandiyah.
e. Masa Pemurnian
Pada masa ini, pengaruh dan praktek-praktek Tasawuf kian
tersebar luas melalui thariqah-thariqah, dan para sulthan serta pangeran tak
segan-segan pula mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka.
Pada masa ini
terlihat tanda-tanda keruntuhan kian jelas, penyelewengan dan sekandal
melanda dan mengancam kehancuran reputasi baiknya dengan ditandainya
munculnya bid’ah, khurafat, mengabaikan syari’at dan hukum-hukum moral dan
penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, berbentangkan diri dari dukungan
awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas, dengan menampilkan amalan yang
irrasional.
Azimat dan
ramalan serta kekuatan ghaib ditonjolkan.[7]
Sehingga muncul Ibn Taimiyah untuk menyerang semua itu, dengan mengembalikan
ajaran tasawuf berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Kepercayaan yang
menyimpang diluruskan, seperti kepercayaan kepada wali, khurafat dan
bentuk-bentuk bid’ah pada umumnya. Menurut Ibn Taimiyah yang disebut
wali (kekasih Allah) ialah orang yang berperilaku baik (shaleh), konsisten
dengan syari’ah Islamiyah. Sebutan yang tepat untuk diberikan kepada
orang tersebut ialah Muttaqin, Allah berfirman dalam surat Yunus (62-63).
62. Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali
Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati. 63. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ibn
Taimiyah mengkritik terhadap ajaran Ittihad, Hulul, dan Wahdat al-Wujud sebagai
ajaran yang menuju kekufuran (atheisme), meskipun keluar dari orang-orang yang
terkenal, arif (orang yang telah mencapai tingkatan Ma’rifat), ahli tahqiq
(ahli hakikat) dan ahli tauhid (yang mengesakan Tuhan). Pendapat tersebut
layak keluar dari mulut orang Yahudi dan Nasrani. Mengikuti pendapat tersebut
hukumnya sama dengan yang menyatakan, yakni kufur. Yang mengikutinya karena
kebodohan, masih dianggap beriman.
[1] Amin Syukur,
Menggugat Tasawuf: Sufisme Dan
Tanggungjawab Social Abad 21, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 18.
[2] Amin Syukur, Masyharuddin, Intelektualisme
Tasawuf-Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), hlm 17.
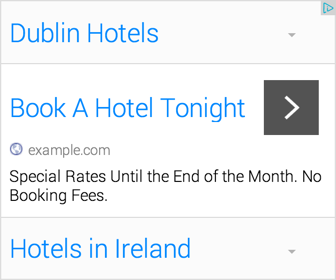
apa landasan amal keagamaan secara sunguh-sungguh yang menjadi motiv zuhud ? yang ada di karakteristik
ReplyDelete